Epstein, Uang dan Impunitas
- account_circle -
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 45
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Epstein memulai kariernya sebagai guru matematika di Dalton School. Meski pria keLahiran Brooklyn 1953 tidak lulus kuliah, namun berkat kegigihannya, ia bisa merambah dunia keuangan di Bear Stearns sebelum mendirikan J. Epstein & Co., perusahaan manajemen kekayaan yang diklaim hanya melayani klien dengan aset di atas US$1 miliar. Jaringan dan Gaya Hidupnya dikenal sebagai sosialita yang memiliki akses ke lingkaran elit global.
Kasus Jeffrey Epstein bukan sekadar skandal kriminal, ia adalah manifestasi paling nyata dari jahatnya relasi elit, fenomena Epstein berdiri sebagai monumen paradoks yang mengguncang euforia francis Fukuyama tentang the end of history. Fukuyama Dalam tesisnya menuliskan optimisme pasca–Perang Dingin, Fukuyama membayangkan liberalisme demokratis dan kapitalisme pasar sebagai horizon final evolusi politik manusia—sebuah titik kulminasi di mana konflik ideologis besar dianggap telah usai.
Namun, figur Epstein justru hadir sebagai anomali nyata yang meruntuhkan keyakinan tersebut. Ia memperlihatkan bahwa sejarah tidak berhenti hanya karena kemenangan liberalisme atau kejayaan kapitalisme semata, namun sejarah selalu berdaptasi dan rutin berganti topeng.
Di permukaan, seakan Epstein tampil sebagai sains modern dengan kedermawanan dia membiayai riset sains mutakhir, teknologi masa depan, dan proyek-proyek intelektual yang menjanjikan kemajuan umat manusia. Universitas-universitas elite dan ilmuwan ternama menyambut dana itu sebagai bahan bakar rasionalitas dan inovasi.
Akan tetapi, di balik topeng filantropi tersebut, Epstein adalah predator sistemik yang memangsa tubuh dan masa depan anak-anak di bawah umur. Kenyataan ini bukan sekadar kontradiksi personal, melainkan fakta dari tatanan liberal-kapitalis itu sendiri—sebuah sistem yang mampu mentransformasikan dana hasil eksploitasi, menjadi narasi kemajuan yang tampak sah, bermoral, bahkan mulia.
Dalam kerangka ini, Epstein bukan penyimpangan dari sistem, melainkan produk ekstremnya. Kapitalisme global tidak hanya menciptakan akumulasi kekayaan, tetapi juga mekanisme pencucian moral (moral laundering) yang memungkinkan kekerasan disublimasikan menjadi prestise intelektual. Dana riset yang mengalir deras ke lembaga-lembaga akademik bukan semata bukti kejayaan rasionalitas modern, melainkan juga tanda kegagalan sistem dalam menyelesaikan janji etisnya sendiri, yaitu melindungi martabat manusia.
Saya mencoba membaca ini Melalui lensa dekonstruksi Derridean, dalam hal ini Epstein dapat dibaca sebagai “hantu” (specter) yang menolak untuk dikuburkan dalam narasi kemenangan liberalisme, Fukuyama mungkin mengira bahwa buku sejarah telah ditutup dengan ditandai oleh satu fakta kemenagan, tetapi Derrida mengingatkan bahwa yang “mati” dalam sejarah tak pernah benar-benar mati.
Ia kembali sebagai residu, sebagai jejak, sebagai gangguan yang menghantui struktur yang mengklaim dirinya mapan. Dalam logika hauntology, Epstein adalah kehadiran yang mengoyak ilusi stabilitas, bukti bahwa kemapanan liberal berdiri di atas fondasi rapuh yang dipenuhi kekerasan laten.
Eksploitasi, ketimpangan, dan impunitas tidak lenyap, mereka hanya disamarkan oleh bahasa filantropi, meritokrasi, dan kemajuan ilmiah. Epstein menjadi simbol bagaimana kekuasaan ekonomi dapat membeli keberpihakan hukum, memanipulasi institusi, dan menghindari pertanggungjawaban selama puluhan tahun.
Fakta bahwa ia nyaris “tak tersentuh” selama beberapa dekade bukan kegagalan individu aparat semata, melainkan cerminan dari ketidakmampuan struktural kapitalisme global untuk menghadirkan keadilan yang substantif. Ketika ideologi tertentu dianggap usang atau berbahaya, justru di situlah ia beroperasi secara diam-diam dalam tubuh sistem dominan.
Dalam konteks ini, kecemasan mayoritas masyarakat terhadap “kebangkitan ideologi kiri” sering kali merupakan proyeksi ketakutan yang keliru. Yang sebenarnya ditakuti bukanlah hantu sosialisme atau egalitarianisme, melainkan pengakuan bahwa sistem dominan telah gagal memenuhi janji moralnya.
Hantu masa lalu—dalam bentuk tuntutan keadilan sosial, kesetaraan struktural, dan pembelaan terhadap yang tertindas—kembali mengetuk kesadaran kolektif bukan sebagai ancaman totalitarian, tetapi sebagai pengingat bahwa hutang sejarah terhadap korban eksploitasi belum pernah dilunasi.
Dekonstruksi, pada titik ini, tidak bisa bersikap netral. Ia menuntut keberpihakan etis. Membongkar status quo Epstein berarti menyingkap relasi kuasa yang selama ini disembunyikan oleh legitimasi akademik dan kekuatan modal.
Jika metafora “malaikat sayap-kiri” dipahami sebagai simbol keberpihakan pada mereka yang dibisukan, para penyintas yang suaranya ditenggelamkan oleh reputasi, jaringan elite, dan kekayaan—maka dekonstruksi menjadi tindakan intelektual yang mendesak dan politis.
Sejarah, dengan demikian, belum dan tidak akan pernah berakhir selama masih ada jeritan ketidakadilan yang bergema di balik dinding-dinding laboratorium megah dan aula universitas prestisius.
Alih-alih meratapi trauma sejarah dengan ketakutan akan perubahan, kita justru diajak untuk berdamai dengan kenyataan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang progresif sering lahir dari upaya meruntuhkan kemapanan yang korup.
Keberpihakan pada kemanusiaan yang transformatif adalah satu-satunya jalan keluar dari siklus ini. Ia menuntut bukan sekadar reformasi simbolik, melainkan pembongkaran struktur yang memungkinkan kekerasan disucikan atas nama kemajuan, padahal contoh yang kini makin jelas, klaim tentang “akhir sejarah” hanyalah fatamorgana; sebuah tirai ideologis yang berusaha menutupi kegelisahan peradaban yang belum selesai berurusan dengan keadilan.
Sejarah akan terus berjalan, selama ada keberanian untuk menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang selama ini bersembunyi di balik cahaya intelektulitas dan uang. Kita mesti terus mengevaluasi apa yang berada dibalik teks itu seperti spirit dekonstruksi, agar kita tidak sekedar dicekoki penghakiman oleh para pemangsa, layaknya Drama kelompok serigala menyelidiki kejahatan serigala, seperti pada drama kasus Epstein ini.
Penulis: Muhammad Kamal
(Alumni PascaSarjana Sosiologi Agama UIN SUKA)
- Penulis: -
- Editor: Suaib PR










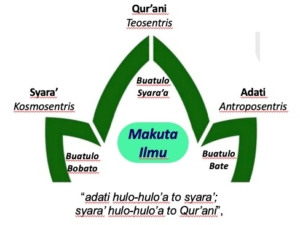

















Saat ini belum ada komentar