NU dalam Cengkeraman Kekuasaan: Ke Mana NU Bergerak?
- account_circle Misbah Yamin
- calendar_month 11 jam yang lalu
- visibility 97
- print Cetak

Ilustrasi : NU dalam Cengkeraman Kekuasaan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Satu abad Nahdlatul Ulama (NU) seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan organisasi keagamaan bertahan dalam lintasan sejarah bangsa, tetapi juga sebagai momentum evaluasi kritis atas arah gerak institusionalnya. Dalam konteks ini, pertanyaan nya “Ke mana NU bergerak?” bukanlah ungkapan emosional, melainkan problem akademik tentang representasi, otonomi organisasi, dan relasi kuasa antara agama dan negara.
Secara historis, NU lahir sebagai organisasi keagamaan berbasis komunitas pesantren dan masyarakat desa. Otoritasnya dibangun dari bawah, melalui legitimasi keilmuan ulama, kepercayaan jamaah, dan keberpihakan sosial terhadap kelompok marginal. Dalam bahasa teori politik, NU berfungsi sebagai aktor civil society yang menjaga jarak kritis dengan negara, sekaligus menjadi kekuatan moral yang mampu mengoreksi kekuasaan.
Dalam dua dekade terakhir, terjadi pergeseran signifikan dalam relasi NU dengan negara. Keterlibatan struktural elite NU dalam pemerintahan baik melalui jabatan menteri, wakil presiden, staf khusus presiden, maupun lembaga negara telah mengubah posisi NU dari mitra kritis menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan itu sendiri. Fenomena ini tampak jelas pada era pemerintahan Joko Widodo, ketika NU secara institusional dan simbolik ditempatkan sebagai pilar legitimasi politik negara.
Penunjukan Ma’ruf Amin, Rais ‘Aam PBNU sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 2019–2024 merupakan titik kulminasi dari proses ini. Secara formal, keterlibatan tersebut sering dibingkai sebagai “kontribusi NU bagi negara”. Namun secara struktural, ia menandai kaburnya batas antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik. Ketika pemegang otoritas tertinggi dalam struktur keulamaan NU berada di jantung kekuasaan negara, maka ruang kritik institusional NU terhadap negara menjadi problematis.
Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan PBNU pasca-Muktamar ke-34 untuk memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah secara hampir tanpa jarak. Berbagai kebijakan negara termasuk yang berdampak langsung pada masyarakat kecil, seperti proyek pembangunan ekstraktif, konflik agraria, dan kebijakan ekonomi neoliberal jarang mendapatkan kritik terbuka dari struktur resmi NU. Sebaliknya, narasi yang dominan adalah stabilitas, moderasi, dan loyalitas kebangsaan.
Di sinilah kritik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menemukan relevansi yang tajam. Gus Dur secara konsisten mengingatkan bahwa organisasi keagamaan akan kehilangan fungsi sosialnya ketika terlalu dekat dengan negara. Dalam esainya “Agama dan Negara”, Gus Dur menegaskan bahwa agama harus menjadi kekuatan korektif, bukan justifikasi kekuasaan. Bagi Gus Dur, keterlibatan politik tidak boleh mengorbankan independensi moral. Ketika NU larut dalam kekuasaan, ia bukan sedang memperkuat negara, melainkan melemahkan dirinya sendiri.
Kritik serupa juga disampaikan oleh Martin van Bruinessen, pengamat NU dan Islam Indonesia, yang mencatat adanya proses oligarkisasi elite keagamaan dalam tubuh NU. Menurutnya, semakin kuat relasi elite NU dengan negara, semakin besar jarak antara pengambil keputusan organisasi dan basis jamaah di akar rumput. NU tetap besar secara simbolik, tetapi melemah secara sosial. Kenyataan di lapangan menunjukkan paradoks ini dengan jelas. Di satu sisi, elite NU memiliki akses luas terhadap sumber daya negara. Di sisi lain, warga NU di pedesaan masih menghadapi persoalan struktural: kemiskinan kronis, pendidikan pesantren yang tertinggal secara ekonomi, serta minimnya perlindungan terhadap petani dan buruh. Persoalan-persoalan ini jarang menjadi agenda utama dalam wacana resmi organisasi. Lebih problematis lagi, kritik internal terhadap arah politik NU sering kali distigmatisasi sebagai ancaman terhadap persatuan jam’iyyah. Mekanisme demokrasi internal melemah, sementara loyalitas struktural lebih dihargai daripada keberanian intelektual. Dalam situasi ini, NU berisiko berubah dari organisasi keagamaan berbasis jamaah menjadi institusi elite yang berbicara atas nama jamaah tanpa proses representasi yang memadai.
Nurcholish Madjid (Cak Nur) telah lama mengingatkan bahaya sakralisasi kekuasaan melalui simbol agama. Ketika agama dipakai untuk melapisi kebijakan negara, maka kritik terhadap kebijakan tersebut mudah dipersepsikan sebagai kritik terhadap agama itu sendiri. Dalam konteks NU, penggunaan simbol keulamaan untuk melegitimasi kekuasaan negara justru menggerus daya kritis warga NU sebagai subjek politik. Dengan demikian, pertanyaan nya “Ke mana NU bergerak?” harus dijawab secara jujur: NU hari ini berada dalam ketegangan antara menjadi organisasi jamaah dan menjadi instrumen legitimasi kekuasaan. Jika kecenderungan ini dibiarkan, NU akan mengalami apa yang oleh Gramsci sebut sebagai hegemoni pasif, ikut menjaga stabilitas sistem tanpa benar-benar mengubah struktur ketidakadilan di dalamnya.
Refleksi satu abad NU seharusnya menjadi titik balik untuk memulihkan kembali otonomi organisasi. NU tidak dituntut untuk menjauh dari negara, tetapi untuk menegaskan kembali posisi kritisnya. Kedekatan dengan istana hanya bermakna jika diimbangi keberanian untuk berbeda, menolak, dan mengoreksi. Surau sebagai simbol basis sosial NU harus kembali menjadi pusat orientasi gerakan. Bukan sebagai romantisme masa lalu, melainkan sebagai kompas etis yang memastikan bahwa setiap langkah politik NU tetap berpijak pada kepentingan jamaah. Tanpa itu, NU akan tetap besar dalam perayaan, tetapi semakin kecil dalam keberpihakan.
Pada akhirnya, pertanyaan ini akan terus menghantui: ketika NU semakin akrab dengan istana, siapa yang benar-benar diwakilinya, negara, elite, atau jamaahnya sendiri?
Penulis : Pengurus Lembaga Kajian Analisis Strategis BEM PTNU Wilayah DI Yogyakarta – Biro Advokasi dan Jaringan PMII Cabang Yogyakarta – Alumni Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta)
- Penulis: Misbah Yamin
- Editor: Djemi Radji









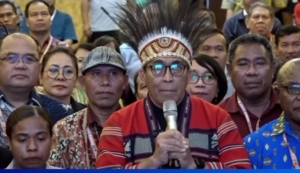


















Saat ini belum ada komentar