Membagun Peradaban Islam yang tak Islami
- account_circle Aljunaid Bakari
- calendar_month Jumat, 14 Jun 2019
- visibility 68
- print Cetak

Aljunaid Bakari, M.Si/ FOTO: Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi merupakan kota yang terus berkembang. Perkembangannya terbilang cukup masif, terutama sejak resmi memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2002. Sebagaimana kota-kota berkembang pada umumnya, arah pengembangan Kota Gorontalo sangat dipengaruhi oleh sense of place—sebuah imaji kolektif yang menjadi inspirasi pembangunan wilayah.
Di banyak kota di Indonesia, sense of place sering bersumber dari adagium atau julukan yang melekat kuat dalam kesadaran masyarakat. Kota Bandung, misalnya, dikenal sebagai “Paris van Java” sehingga arah pengembangannya banyak menonjolkan citra kota mode dan pariwisata kreatif.
Dalam konteks Kota Gorontalo, adagium yang paling kuat melekat adalah “Serambi Madinah”. Imaji ini berkontribusi besar dalam membentuk sense of place Kota Gorontalo dan menjadi rujukan pengembangan kota berbasis ethical society. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dijadikan fondasi utama dalam pembangunan wilayah, sehingga corak pengembangan kota diarahkan menyerupai karakter Kota Madinah.
Persoalannya muncul ketika citra keislaman tersebut ditafsirkan secara kaku oleh para pemangku kepentingan. Pengembangan kota cenderung direduksi pada pembangunan infrastruktur fisik semata, sementara aspek ekologis, kultural, dan sosial justru terabaikan. Kota seolah “dipaksa bersolek” secara simbolik, namun kehilangan ruh nilai-nilai Islam yang sesungguhnya.
Sejarah kota-kota besar dunia memberikan pelajaran penting. Kota Baghdad, yang pernah dikenal sebagai pusat peradaban dan keilmuan dunia—kota “1001 malam”—mengalami kemunduran ketika pembangunan material dan fisik lebih dominan dibanding penguatan tradisi keilmuan dan kultural yang menjadi fondasi kejayaannya.
Arah pengembangan Kota Gorontalo saat ini tampak mengarah pada kesalahan yang serupa. Salah satu indikatornya adalah alih fungsi lahan pertanian produktif yang terjadi secara masif seiring pembangunan infrastruktur kota. Yang paling mencolok adalah rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun Islamic Center di atas lahan persawahan produktif seluas 13 hektare milik warga di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur.
Alih-alih membawa maslahat, rencana ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama banjir yang semakin sering melanda berbagai kelurahan dan pusat kota. Banjir ini terjadi akibat alih fungsi lahan yang mengurangi daya resap air, sementara kapasitas sungai dan drainase tidak mampu menampung debit air yang meningkat. Secara umum, banjir di Kota Gorontalo disebabkan oleh faktor alam dan, yang lebih dominan, oleh aktivitas manusia.
Pada titik ini, rencana pembangunan Islamic Center patut dipersoalkan dan dievaluasi secara menyeluruh. Bahkan, wajib ditolak jika terbukti lebih banyak mendatangkan mudarat daripada maslahat bagi warga Kota Gorontalo.
Beberapa poin krusial yang perlu menjadi perhatian serius antara lain:
Pertama, Kota Gorontalo hampir setiap musim hujan menjadi langganan banjir. Hal ini menuntut evaluasi serius terhadap tata kelola lahan perkotaan. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 40 Tahun 2011, lahan produktif di empat kecamatan—Dungingi, Kota Tengah, Kota Utara, dan Kota Timur—ditetapkan sebagai kawasan resapan air. Jika alih fungsi lahan terus dibiarkan, maka pelanggaran terhadap rencana tata ruang harus dihentikan secara tegas.
Kedua, alih fungsi lahan persawahan untuk pembangunan Islamic Center sangat kontraproduktif dengan upaya penanggulangan banjir. Sawah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan dan penghidupan masyarakat, tetapi juga sebagai kawasan resapan air paling efektif. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Secara hidrologis, satu hektare sawah dengan sistem irigasi konvensional membutuhkan sekitar 1.157 liter air per detik atau sekitar 100.000 liter per hari. Dengan luasan 13 hektare, terdapat siklus hidrologi alami sekitar 1,3 juta liter air per hari. Jika lahan ini dialihfungsikan, maka alokasi air akan berpindah ke wilayah lain melalui drainase, yang pada musim hujan menjadi penyumbang utama genangan dan banjir di berbagai titik kota.
Ketiga, alih fungsi lahan ini menghilangkan sumber penghidupan utama petani. Berdasarkan data BPS dengan metode ubinan KSA, produktivitas padi sawah di Kota Gorontalo tahun 2018 mencapai rata-rata 5,2 ton per hektare. Dengan luasan 13 hektare, potensi hasil panen mencapai sekitar 68 ton gabah per musim.
Jika dikonversi dengan harga gabah Maret 2019 sebesar Rp4.200 per kilogram, maka potensi pendapatan petani mencapai sekitar Rp285,6 juta per panen, atau Rp856,8 juta per tahun dengan tiga kali panen. Pemerintah semestinya menjamin pendapatan setara bagi petani yang kehilangan mata pencaharian akibat alih fungsi lahan tersebut.
Keempat, memaksakan pembangunan infrastruktur di atas lahan pertanian produktif yang telah dilindungi regulasi justru mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Cara semacam ini tidak sejalan dengan prinsip keislaman.
Dalam kaidah ushul fikih ditegaskan: Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih—menolak kemudaratan harus didahulukan daripada meraih kemanfaatan. Prinsip ini seharusnya menjadi landasan utama kebijakan publik di daerah yang mengusung identitas religius.
Mencegah kerusakan lingkungan, kehilangan sumber ekonomi masyarakat, serta dampak sosial yang luas jauh lebih Islami daripada sekadar membangun simbol keislaman yang justru menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan.
Penulis adalah Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim PWNU Gorontalo
- Penulis: Aljunaid Bakari
- Editor: Aljunaid Bakari
























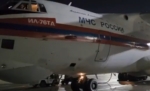


Saat ini belum ada komentar