Rajab dan Kepulangan yang Sunyi: Bayi, Pohon, dan Rahmat Tuhan
- account_circle Afidatul Asmar
- calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
- visibility 166
- print Cetak

Kolase : Afidatul Asmar/ Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Rajab selalu datang dengan sunyi yang disengaja. Ia tidak meminta sorak, hanya ruang untuk merenung. Di bulan inilah sebuah budaya tentang kematian bayi di Toraja yang belum tumbuh gigi dan “dipulangkan” ke pohon mengajak kita menimbang ulang makna hidup, iman, dan kemanusiaan.
Rajab adalah bulan yang tidak riuh. Ia berdiri tenang di antara kalender hijriah, seolah sengaja memberi jeda sebelum manusia berlari lebih jauh. Dalam tradisi Islam, Rajab dimuliakan sebagai bulan haram, bulan untuk menahan diri, memperbanyak istighfar, dan melunakkan hati. Pada ruang sunyi itulah sebuah budaya tentang tradisi kematian bayi di Tana Toraja menemukan maknanya.
Bayi yang meninggal sebelum tumbuh gigi, dalam tradisi Toraja, tidak dikuburkan sebagaimana orang dewasa. Ia ditempatkan di batang pohon Tarra melalui ritual Passiliran. Bayi itu tidak disebut “meninggal”, melainkan “pulang”. Pohon menjadi rahim kedua; getahnya dimaknai sebagai susu. Alam melanjutkan peran yang tak sempat dituntaskan manusia.
Bagi nalar modern, praktik ini kerap dianggap eksotis, bahkan problematik. Namun Rajab mengajarkan satu kebijaksanaan penting: tidak semua perbedaan harus disikapi dengan penghakiman. Sebagian justru perlu dibaca dengan empati.
Dalam Islam, hidup dan mati berada dalam ketetapan Allah yang penuh hikmah (QS. Al-Hadid: 22). Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (HR. Bukhari–Muslim). Bayi yang wafat tidak menanggung dosa sosial, tidak memikul beban sejarah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa anak yang meninggal dapat menjadi syafaat bagi orang tuanya (HR. Ahmad). Artinya, kematian bayi bukan ruang hukuman, melainkan lanskap rahmat.
Di titik inilah Passiliran menemukan resonansi etiknya. Meski berbeda bentuk dengan penguburan Islam, pesan kemanusiaannya sejalan: memuliakan jiwa yang masih suci dan menerima kematian sebagai kepulangan, bukan sekadar kehilangan.
Kajian antropologi menunjukkan bahwa hampir semua kebudayaan memiliki ritual khusus bagi kematian bayi. Mary Douglas menyebutnya sebagai upaya masyarakat menempatkan peristiwa “antara” belum sepenuhnya hidup sosial, namun telah pergi. Victor Turner menyebutnya fase liminalitas, ruang simbolik yang sarat makna. Dalam Passiliran, pohon Tarra bukan benda mati, tetapi makhluk hidup yang tumbuh. Seiring batangnya membesar, tumbuh pula keyakinan bahwa jiwa bayi menyatu dengan ritme alam.
Psikologi modern membaca ritual semacam ini sebagai proses meaning-making dalam menghadapi duka. Ritual membantu keluarga berdamai dengan kehilangan, memberi struktur emosi, dan mencegah duka jatuh ke kehampaan. Maka Passiliran bekerja bukan hanya secara spiritual, tetapi juga psikososial.
Islam sendiri menempatkan penguburan di tanah sebagai praktik normatif. Al-Qur’an menyebut tanah sebagai asal penciptaan dan tempat kembali manusia (QS. Thaha: 55). Tanah adalah simbol kerendahan dan kepasrahan. Namun Islam juga menekankan bahwa hakikat pemakaman bukan pada medium fisiknya, melainkan pada pemuliaan jenazah dan niat penghormatan. Bayi yang wafat dipandang suci; ruhnya berada dalam rahmat Allah.
Dari sini, dakwah budaya menemukan jalannya. Islam tidak hadir untuk menertawakan tradisi, tetapi meluruskannya secara tauhid. Pohon Tarra dan tanah sama-sama ciptaan Allah. Keduanya hanyalah simbol. Yang menerima kembali jiwa bayi bukan pohon dan bukan tanah, melainkan Allah Yang Maha Pengasih. Dakwah bekerja bukan dengan palu vonis, melainkan dengan cahaya makna.
Sejarah Islam mencatat bahwa para sahabat Nabi pun mengalami kehilangan anak. Rasulullah SAW tidak meniadakan kesedihan mereka. Beliau menangis, namun tidak larut. Islam mengajarkan keseimbangan: berduka tanpa putus asa, ikhlas tanpa meniadakan rasa. Etika inilah yang, secara kultural, juga tampak dalam Passiliran: tanpa ratapan berlebihan, tanpa dramatika hanya penerimaan.
Dalam perjalanan perenungan penulis berpandangan antropologi dan dakwah dapat menemukan jalan dengan cara yang pelan dan menyentuh: bahwa yang paling religius sering kali bukan yang paling lantang, melainkan yang paling lembut menjaga kehidupan. Pohon Tarra berdiri dalam sunyi seperti itu tanpa khutbah, tanpa fatwa namun menghadirkan pelajaran tentang kasih.
Rajab, pada akhirnya, bukan sekadar nama bulan. Ia adalah undangan untuk menepi dan menimbang ulang. Budaya tentang bayi yang belum bergigi itu bukan hanya kisah Toraja, tetapi cermin nurani kita bersama: sudahkah kita memuliakan kehidupan, bahkan ketika ia hanya singgah sebentar?
Bulan Rajab ini, barangkali kita tidak perlu banyak jawaban. Cukup keberanian untuk diam sejenak, mendengar, dan belajar dari kepulangan yang sunyi namun penuh rahmat. Karena dakwah yang paling dalam sering lahir bukan dari penghakiman, melainkan dari empati yang menjaga iman dan kemanusiaan tetap sejalan.
Bulan Rajab ini, barangkali kita juga diajak untuk menata ulang cara beragama: tidak tergesa menilai, tidak sibuk mengoreksi, dan tidak mudah mengklaim kebenaran secara sepihak. Rajab mengajarkan jeda bahwa iman yang matang tumbuh dari kesanggupan memahami kenyataan hidup orang lain, termasuk kenyataan budaya yang membingkai duka dan kehilangan. Dari sana, dakwah menemukan wajahnya yang paling bersahabat: hadir sebagai penerang jalan, bukan sebagai hakim yang berdiri di garis akhir.
Kepulangan bayi yang sunyi itu entah melalui tanah atau pohon mengingatkan kita bahwa hidup manusia, betapapun singkat, selalu layak dimuliakan. Agama dan budaya, bila dipertemukan dengan niat yang jernih, dapat saling menjaga agar kemanusiaan tidak kehilangan arah dan iman tidak kehilangan kelembutan. Maka Rajab bukan hanya bulan yang dimuliakan, tetapi juga kesempatan untuk belajar menjadi manusia yang lebih rendah hati: yang berani diam, mendengar, dan percaya bahwa rahmat Tuhan sering kali bekerja dalam cara-cara yang tidak berisik, namun menenangkan.
Penulis : Dosen & Peneliti Bidang Antropologi Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare/ Alumni PPNK LEMHANNAS RI
- Penulis: Afidatul Asmar
- Editor: Afidatul Asmar

























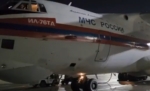


Saat ini belum ada komentar