Paradigma yang Berkembang: Menempatkan “Mahkota Ilmu” sebagai Proses Dialektis-Epistemologis
- account_circle Donald Qomaidiasyah Tungkagi
- calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
- visibility 278
- print Cetak

Keterangan Gambar : Simbol "Makuta" berwarna hijau dari Dr. Andries Kango, yang diperkaya konseptualisasi dari penulis.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pengantar
Tulisan ini merupakan respon atas kritik Tarmizi Abbas terhadap sanggahan saya sebelumnya. Ia menulis sangat baik, “Tak Ada Yang Integratif Dari ‘Epistemologi Integratif’ dalam Paradigma Makuta Ilmu: Itu Kesesatannya” (10 Januari 2026) di nulondalo.com. Saya tetap mengapresiasi, serta belajar banyak hal dari kritik tersebut. Sebelumnya, diskursus melalui beberapa tulisan dengan Tarmizi Abbas, dipantik dari tulisan saya tentang menawarkan Makuta Ilmu, dibalas dengan kritik tajam, selanjutnya sanggahan saya, hingga kritik lanjutannya, setidaknya telah menjadi ruang belajar yang berharga. Tegangan-tengangan yang muncul dalam narasi berbalas dalam tulisan tersebut saya anggap sebagai tegangan produktif.
Sekadar menegaskan hal yang mungkin luput dari tulisan saya sebelumnya bahwa paradigma “Mahkota Ilmu”, merupakan tawaran yang masih terus berkembang sebagai proses dialektis-epistemologis. Sejak awal ini memang proses yang belum selesai, dan tentunya terbuka untuk diperdebatkan. Paradigma ini diharapkan terus diperkaya, diperdebatkan, dan disempurnakan melalui dialog akademik, bahkan diganti jika memang ada paradigma yang lebih baik dan relevan.
Paradigma ini sengaja ditawarkan sebagai pemantik diskusi, tujuannya memang untuk dikritisi. Pancingan seperti ini dibutuhkan di tengah menguatnya gejala dalam lingkungan akademik kita yang seakan terjebak dalam critical paralysis, kondisi kapasitas mengkritisi yang dominan tapi minim produksi gagasan baru. Biasanya ditandai dengan seringkali kita lebih mudah mengkritisi ketimbang memulai hal baru untuk dikritik.
Saya belajar bahwa sebuah paradigma keilmuan, tidak jauh berbeda dengan pengetahuan itu sendiri, tidak pernah lahir dalam kondisi sempurna ataupun final. Pengetahuan selalu lahir dari pergulatan bahkan “baku-hantam” intelektual yang panjang, dan tentunya perlu dimulai dari keberanian untuk merumuskan sesuatu meski mungkin masih tampak kasar dan banyak celah kritiknya. Paradigma “Mahkota Ilmu” dalam konteks sebagai kerangka epistemologis UIN Sultan Amai Gorontalo adalah upaya semacam itu, merupakan tawaran yang ditelurkan dari rahim kegelisahan dan dilandasi niatan memberikan kontribusi pada perbincangan akademik perihal identitas keilmuan universitas Islam di Indonesia secara umum.
Tulisan ini menghindari respon konfrontatif, yang ada justru lebih condong mengklarifikasi posisi saya yang secara sadar tidak menempatkan tawaran paradigma “Mahkota Ilmu” sebagai produk final yang harus dipertahankan mati-matian. Untuk itu, saya merasa perlu terlebih dahulu menjelaskan kembali posisi “makuta” dalam paradigma “Mahkota Ilmu”.
Paradigma Sebagai Proses: Dari Makuta ke Mahkota Ilmu
Pada tulisan kedua, saya sudah mulai menggunakan “Mahkota Ilmu” sebagai pengganti “makuta ilmu”, peralihan kata dari bahasa lokal menjadi nasional, belum lama sejak kelahirannya merupakan bukti konsep ini terbuka dalam perubahan. Perjalanan perumusan paradigma ini dimulai dari ketertarikan pada desain logo yang menggunakan simbol “makuta” (silahkan baca tulisan awal). Ketertarikan ini bukan pada aspek visual, melainkan pada potensi filosofis yang ada dalam kata “makuta atau dalam bahasa Indonesia mahkota”. Bagi saya mahkota bukan sekadar hiasan kepala, melainkan representasi dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Mahkota dalam konteks ini sebagai metafora kerangka epistemologis paradigma UIN Gorontalo.
Term “Mahkota Ilmu” sebagai representasi dari posisi ilmu pengetahuan dalam peradaban: “ilmu harus dijunjung tinggi, ditempatkan di puncak kepala sebagaimana mahkota yang melambangkan kehormatan dan tanggung jawab”. Metafora Makuta, sebagai upaya untuk menerjemahkan nilai luhur ini dalam bahasa simbolis yang berakar pada budaya lokal Gorontalo.
Makuta dalam konteks saat ini—bukan historis: “paluwala dari kerangka daun dan ranting—secara visual (maupun simbolis) tampak memiliki tiga pilar. Tiga pilar ini yang kemudian dijadikan sebagai representasi dari tiga dimensi epistemologis yang diintegrasikan dalam paradigma keilmuan UIN. Ini juga perlu ditegaskan dengan jelas bahwa tiga pilar ini adalah simbolisasi, tidak bisa serta merta dianggap sebagai identifikasi yang kaku dan satu-satu. Sederhananya, pilar-pilar dalam makuta menjadi representasi visual untuk mengakomodasi tiga dimensi pengetahuan yang berasal dari dua warisan penting dalam tradisi masyarakat Gorontalo. Pertama adalah falsafah Adati hula-hula to sara’a, sara’a hula-hula to Qur’ani—selanjutnya ABSSBQ, yang menunjukkan adanya tiga dimensi yang saling terkait: adat, syariat, dan Al-Qur’an. Tarmizi boleh saja skeptis tentang keberadaan falsafah ini, tapi bagi saya kekurangan referensi tertulis tidak serta merta menafikan keberadaan tahuda (falsafah adat) yang telah dikenal hingga mengakar dalam kebudayaan masyarakat Gorontalo saat ini. Kedua adalah struktur pemerintahan tradisional yang dikenal sebagai Buatulo Toulongo, yaitu tiga pilar pemerintahan: Syara’a (ulama), Bubato (pemerintah), dan Bate (pemuka adat) sebelumnya ditempati Bala (keamanan).
Bagi saya, meski tetap bisa diperdebatkan, kedua warisan tersebut justru menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo telah mengenal konsep integrasi antara berbagai dimensi kehidupan: yang sakral dan yang profan, yang transenden dan yang imanen, yang normatif dan yang empiris. Artikulasi ini yang kemudian diejawantah dalam kerangka epistemologis yang lebih sistematis dengan menggunakan terminologi teo-antropo-kosmosentris. Saya uraikan kembali sebagai berikut:
Pilar pertama, dimensi teosentris, merepresentasikan orientasi epistemologis yang berpusat pada Tuhan dan wahyu. Ini adalah dimensi yang dalam ABSSBQ direpresentasikan oleh Al-Qur’an (Qur’ani), sumber tertinggi pengetahuan dan nilai. Namun lebih dari itu, dimensi teosentris juga mencakup cara pandang yang menempatkan Tuhan sebagai sumber dan tujuan akhir dari seluruh pengetahuan manusia. Pilar kedua, dimensi kosmosentris, merepresentasikan orientasi epistemologis yang berpusat pada alam semesta dan fenomena empiris. Dalam tradisi ABSSBK, ini direpresentasikan oleh syara’, yang meskipun berbasis pada wahyu, dalam praktiknya selalu responsif terhadap realitas empiris dan konteks sosial-budaya. Saya memahami bahwa ada perdebatan tentang apakah syara’ bisa merepresentasikan kosmosentrisme, mengingat basis keduanya berbeda. Namun yang saya maksudkan di sini adalah bahwa syara’, khususnya dalam tradisi fiqh, selalu mempertimbangkan maqashid (tujuan), maslahah (kemaslahatan), dan konteks sosio-kultural, yang berarti ia tidak bisa dilepaskan dari pembacaan terhadap realitas kosmis dan empiris. Pilar ketiga, dimensi antroposentris, merepresentasikan orientasi epistemologis yang berpusat pada manusia, budaya, dan masyarakat. Dalam tradisi ABSSBK, ini direpresentasikan oleh adat, nilai-nilai, norma, dan praktik yang hidup dalam masyarakat.
Ketiga dimensi ini bukan entitas yang terpisah dan berdiri sendiri. Mereka saling terkait, saling mempengaruhi, dan dalam praktiknya seringkali tumpang tindih. Simbolisasi melalui tiga pilar makuta justru ingin menunjukkan bahwa meskipun berbeda, ketiganya menyatu dalam satu struktur yang kokoh, seperti mahkota yang indah justru karena harmoni dari berbagai elemennya.
Jika dikembangkan lebih jauh, konsep tiga pilar ini juga memiliki kesesuaian secara tidak langsung dengan kerangka epistemologis “Ilmu Sosial Profetik” yang dikembangkan Kuntowijoyo (2006). Kerangka ini terdiri dari trilogi profetik: humanisasi, liberasi dan transendensi. Humanisasi bertujuan untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan segala bentuk dehumanisasi (keterasingan, penindasan, materialisme). Liberasi fokus pada membebaskan dari struktur sosial yang menindas, baik politik, ekonomi, budaya, maupun ilmu pengetahuan itu sendiri. Transendensi berfokus pada mengarahkan segala perubahan tidak hanya pada tujuan duniawi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Memberikan basis moral-transendental pada humanisasi dan liberasi, sekaligus mengingatkan bahwa manusia memiliki dimensi spiritual.
Pembuktian yang Keliru Dipahami
Bagi Tarmizi, saya telah gagal membuktikan akar historis makuta dalam tradisi intelektual Gorontalo. Sembari mempertanyakan: “Pertanyaan penting yang saya ingin ajukan lagi: memang, di mana akarnya? Itu yang harusnya ia jawab.” Di sinilah terjadi kesalahpahaman mendasar tentang pembuktian (burden of proof) dalam konteks konstruksi paradigma epistemologi.
Pertama, saya perlu menjelaskan konteksnya, ketika saya mengatakan: “makuta adalah cerminan dari nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam tradisi intelektual masyarakat Gorontalo”, yang dimaksud adalah makuta sebagai bagian dari tradisi Gorontalo yang bertahan dan kita nikmati saat ini. Kata “intelektual” dalam pernyataan itu yang mungkin menimbulkan salah persepsi. Meski begitu, makuta yang ada dalam konteks saat ini tentunya tidak lepas juga dari hasil pergulatan historis. Untuk ini, pada tulisan sebelumnya saya telah menegaskan: “…tidak bisa dinafikan juga “makuta” kini dengan segala adaptasinya justru telah menjadi bagian dari budaya Gorontalo”. Keberadaan makuta yang memiliki tiga bagian sebagaimana yang tampak saat inilah yang dijadikan sebagai simbolisasi “Mahkota Ilmu”.
Maka, “makuta” dalam paradigma “Mahkota Ilmu” disini harus dipahami bukan sebagai representasi autentik yang steril dan esensialis, melainkan sebagai produk dialektika historis yang terus berkembang. Artinya, makuta dengan sejarahnya yang begitu kompleks, sebagaimana telah diurai dalam tulisan sebelumnya dari paluwala hingga bentuknya yang sekarang, justru mencerminkan perjalanan dialektis historis masyarakat Gorontalo itu sendiri. Ini mungkin diantara perbedaan pendekatan saya dengan esensialisme kultural yang jadi objek kritik Tarmizi.
Selanjutnya, Tarmizi juga mengkritisi bahwa interpretasi saya terhadap Kuhn keliru. Sembari mengutip Kuhn dengan menulis paradigma bukan “…alat untuk mengamati masalah-masalah ilmiah, melainkan melihat: (1) apa yang boleh disebut masalah; (2) bagaimana cara menyelesaikannya; (3) bagaimana komunitas ilmiah bekerja.” Saya justru agak heran dengan kritik ini. Padahal ketiga hal yang disebutkan itu justru termasuk dalam fungsi paradigma sebagai “teropong” (framework) untuk memahami fenomena ilmiah yang saya maksud. Ketika saya mengatakan “fungsi paradigma sebagai teropong untuk mengamati dan memahami masalah-masalah ilmiah,” justru sedang merujukan pada ketiga fungsi paradigma tersebut. Seharusnya ini tidak dianggap sebagai kontradiksi, melainkan cara berbeda dalam memahami dan mengekspresikan objek yang sama.
Tarmizi kemudian menulis: “Justru, sejarah dalam perkembangan paradigma a la Kuhnian adalah titik kunci memahami bagaimana paradigma pengetahuan berkembang dan bersitegang melalui normal science, anomali dan krisis, revolusi ilmiah.” Pada bagian ini saya sepenuhnya sependapat. Sebab, ini justru mendukungan argumen saya bahwa paradigma berkembang melalui ketegangan, anomali, dan krisis, sejalan ketegangan antara tiga pilar dalam Makuta Ilmu yang justru produktif, bukan destruktif.
Ketegangan Produktif versus Kontradiksi: Paradigma Sebagai Ruang Dialog
Ini yang terus diulang, Tarmizi tetap bersikukuh bahwa tiga pilar dalam Mahkota Ilmu, teo-antropo-kosmosentris, “secara tegas saling menegasikan satu sama lain.” Ia menolak konsep “jembatan” yang digagas dalam integrasi tersebut dengan pertanyaan retoris: “Bagaimana jika nanti di tengah jembatan keduanya justru bakuhantam, alih-alih dialog, saling peluk dan jabat tangan?”
Saya kira, pertanyaan ini justru menunjukkan pemahaman yang terlalu simplistik terhadap integrasi epistemologis. Berkaca pada paradigma integrasi-interkoneksi misalnya, jembatan yang dimaksud disini bukanlah ruang di mana perbedaan dihilangkan, apalagi sampai semua hal harus “saling peluk dan jabat tangan.” Jembatan disini sebagai metafora adanya ruang dialog kritis di mana berbagai perspektif keilmuan saling berinteraksi, saling mengkritik, dan kemudian diharapkan dalam prosesnya menghasilkan pemahaman yang lebih utuh.
Tidak menutup kemungkinan bakal ada yang “bakuhantam” di tengah dialog, kalaupun terjadi, itu justru bukan masalah. Justru dari “pergulatan, pergumulan, bahkan pertempuran” intelektual semacam itulah ilmu pengetahuan jadi kian berkembang. Ini yang saya pahami dari paradigma Kuhn bahwa dengan perkembangan sains melalui anomali dan krisis, yang kemudian oleh Amin Abdullah disebut ketegangan produktif dalam paradigma integrasi-interkoneksi.
Kritik Tarmizi berlanjut dengan memberikan contoh fiqh lingkungan dan ekoteologi, lalu mengkritik bahwa organisasi keagamaan juga memegang konsesi tambang yang merusak lingkungan. Ia bertanya: “Di titik ini, bukankah yang terjadi adalah keselarasan semu?” Saya harus mengakui kalau kritik ini valid dalam tataran praktik. Sampai disitu. Kritik ini menjadi keliru ketika dijadikan sebagai landasaan argumentasi untuk menolak kemungkinan dialog teoretis dalam paradigma Mahkota Ilmu.
Adanya inkonsistensi praktik dengan teori, tidak lantas membatalkan sebuah paradigma integratif. Jika logika ini diikuti, berapa banyak paradigma atau konsep yang harus ditolak karena inkonsistensi dalam praktik? Haruskah kita menolak demokrasi karena banyak negara dengan sistem ini yang tidak demokratis? Banyaknya manusia berperilaku tidak etis, sebagai contoh Trump yang menangkap Presiden Venezuela, tidak berarti kita harus menghilangkan konsep etika.
Memang diakui, ketegangan antarpilar dalam Mahkota Ilmu benar adanya, namun bukan saling menegasikan, melainkan jadi motor penggerak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Semisal, ketika perspektif teosentris (agama) berhadapan dengan temuan-temuan empiris dari perspektif kosmosentris, yang terjadi bukan harus berujung pada penolakan salah satu, melainkan pencarian sintesis yang lebih tinggi. Isu lingkungan sebagai contoh, ketika perspektif teosentris menekankan konsep khalifah fil ardh dan tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan; peran perspektif kosmosentris disini adalah menyediakan data empiris tentang kerusakan ekologis dan dampaknya; selanjutnya perspektif antroposentris mengangkat praktik-praktik lokal dalam mengelola alam. Dialog antara ketiga perspektif ini, meskipun dalam tataran epistemologis penuh ketegangan, ini justru bisa menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan solusi yang lebih adil bagi setiap persoalan.
Dekolonial: Pisau Analisis, Bukan Paradigma Utama
Ketika Tarmizi mengusulkan dekolonial sebagai paradigma (utama), saya berpendapat sebaliknya bahwa dekolonial lebih tepat diposisikan sebagai salah satu metode atau pisau analisis saja tinimbang sebagai paradigma utama itu sendiri. Saya ingin meminjam kritik Nadia Altschul dalam “The Decolonial Imperative: A Postcolonial Critique” (2022), sebagai pijakan argumentasi mengapa dekolonial dalam konteks ini hanya sebatas pisau analisis pelengkap, sebagai berikut:
Pertama, Altschul menunjukkan bahwa “gerakan dekolonial seringkali lebih sibuk memperebutkan otoritas epistemik ketimbang benar-benar membebaskan pengetahuan dari belenggu kolonial.” Dari sini terdapat potensi ketika menawarkan perspektif dekolonial sebagai paradigma utama, justru berisiko menjadi alat untuk mendiskreditkan bentuk-bentuk pengetahuan lain yang dianggap “tidak cukup dekolonial”, meskipun nanti ketika pengetahuan tersebut sebenarnya justru berakar pada tradisi lokal.
Kedua, Altschul dalam artikelnya mengutip pernyataan Grosfoguel, salah satu tokoh dekolonial terkemuka. Grosfoguel justru mengakui bahwa tidak ada satu pun dari teoritikus dekolonial, termasuk dirinya sendiri, yang bisa mengklaim telah sepenuhnya terberbas dari kolonialitas. Dengan demikian, bagaimana bisa kita menjadikan dekolonialitas sebagai paradigma utama yang seolah-olah sudah bersih dari kolonialitas, sedangkan para tokohnya mengakui tidak terbebas dari kolonialitas? Dari sini jadi paradoks yang tidak bisa diabaikan. Maka, lebih bijak ketika memposisikan dekolonialitas sebagai salah satu perspektif kritis untuk memperkaya paradigma, bukan sebagai paradigma utama itu sendiri.
Ketiga, kritik ini yang paling fundamental dalam konteks UIN, sebagaiman disebutkan, dekolonialitas mengklaim ingin “melepaskan diri” (de-linking) dari narasi dominan (Mignolo & Walsh, 2018). Perspektif dekolonial yang konsisten pada de-linking, akhirnya akan menolak posisi wahyu atau Al-Qur’an sebagai narasi dominan atau landasan epistemologis utama. Jati diri dekolonial yang merupakan kritik terhadap fundamentalisme dan monopoli kebenaran akan diterapkan juga pada klaim kebenaran wahyu. Dekolonial meniscayakan pluralitas epistemologis tanpa hierarki. Ini justru bertolak belakang dengan basis keilmuan UIN itu sendiri yang memang menempatkan Al-Qur’an atau wahyu sebagai penuntun pengetahuan, dengan segala argumentasi teologis dan epistemologisnya. Paradigma integrasi-interkoneksi di UIN-UIN Indonesia sejak awal dibangun dengan kesadaran bahwa wahyu adalah sumber pengetahuan yang memiliki posisi puncak utama. Penempatan pilar “teosentris” sebagai pilar utama dalam “Mahkota Ilmu” merupakan ejawantah dari wahyu memandu ilmu ini.
Meski demikian, tidak berarti kritik dekolonial tidak relevan dalam konteks UIN. Kritik dekolonial justru sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa komitmen pada wahyu tidak berubah menjadi fundamentalisme yang menutup ruang dialog dan interpretasi. Meski, tetap dengan tekanan bahwa dekolonial tidak bisa menjadi paradigma utama karena secara fundamental bertentangan dengan karakter UIN sebagai universitas Islam.
Penutup: Mahkota sebagai Tanggung Jawab
Jika ditelusuri dalam tradisi manapun, mahkota dipahami bukan sebatas simbol kehormatan semata, melainkan juga simbol tanggungjawab. Raja yang bermahkota bukan hanya menikmati privilege, tetapi juga memikul amanah yang berat untuk rakyatnya. Demikian pula dengan “Mahkota Ilmu”, secara filosofis menempatkan ilmu di posisi terhormat, seturut kemudian berarti juga memikul tanggung jawab besar: tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu dengan sungguh-sungguh, menjaganya, serta berkontribusi pada masyarakat, dan untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Tuhan.
IAIN dalam momentum transformasinya menjadi UIN Sultan Amai Gorontalo, tentunya memiliki kesempatan emas untuk merumuskan identitas keilmuannya sendiri. “Mahkota Ilmu” merupakan sebuah tawaran, berangkat dari kegelisahan intelektual, ditarik dari tradisi lokal, serta senantiasa terbuka pada dialog dengan perspektif global, dan yang berkomitmen pada nilai-nilai spiritual Islam. Selanjutnya, apakah tawaran ini akan diterima, dikembangkan, atau bahkan diganti dengan paradigma yang lebih baik, itu soal lain. Setiap tawaran untuk sebuah institusi akademik tentunya adalah keputusan kolektif yang perlu diambil melalui dialog yang matang dan mendalam.
Terpenting dan utama, proses pencarian paradigma keilmuan merupakan proses yang penting dan tidak boleh diabaikan. Bahkan seharusnya didahulukan dari penentuan logo dan lagu mars UIN itu sendiri. Bagaimanapun, tanpa paradigma yang jelas, transformasi menjadi UIN hanya akan menjadi perubahan nama dan struktur administratif, tanpa perubahan substansial dalam cara kita memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di titik ini, itu justru akan menjadi tragedi intelektual yang disayangkan. Semoga tidak demikian. Tabe!
Penulis : Dosen Prodi Sosiologi Agama IAIN Sultan Amai Gorontalo
- Penulis: Donald Qomaidiasyah Tungkagi
- Editor: Donald Qomaidiasyah Tungkagi





















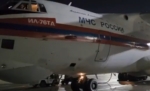




Saat ini belum ada komentar