Ekoteologi sebagai Upaya Resakralisasi Alam
- account_circle Pepi Al-Bayqunie
- calendar_month 6 jam yang lalu
- visibility 29
- print Cetak
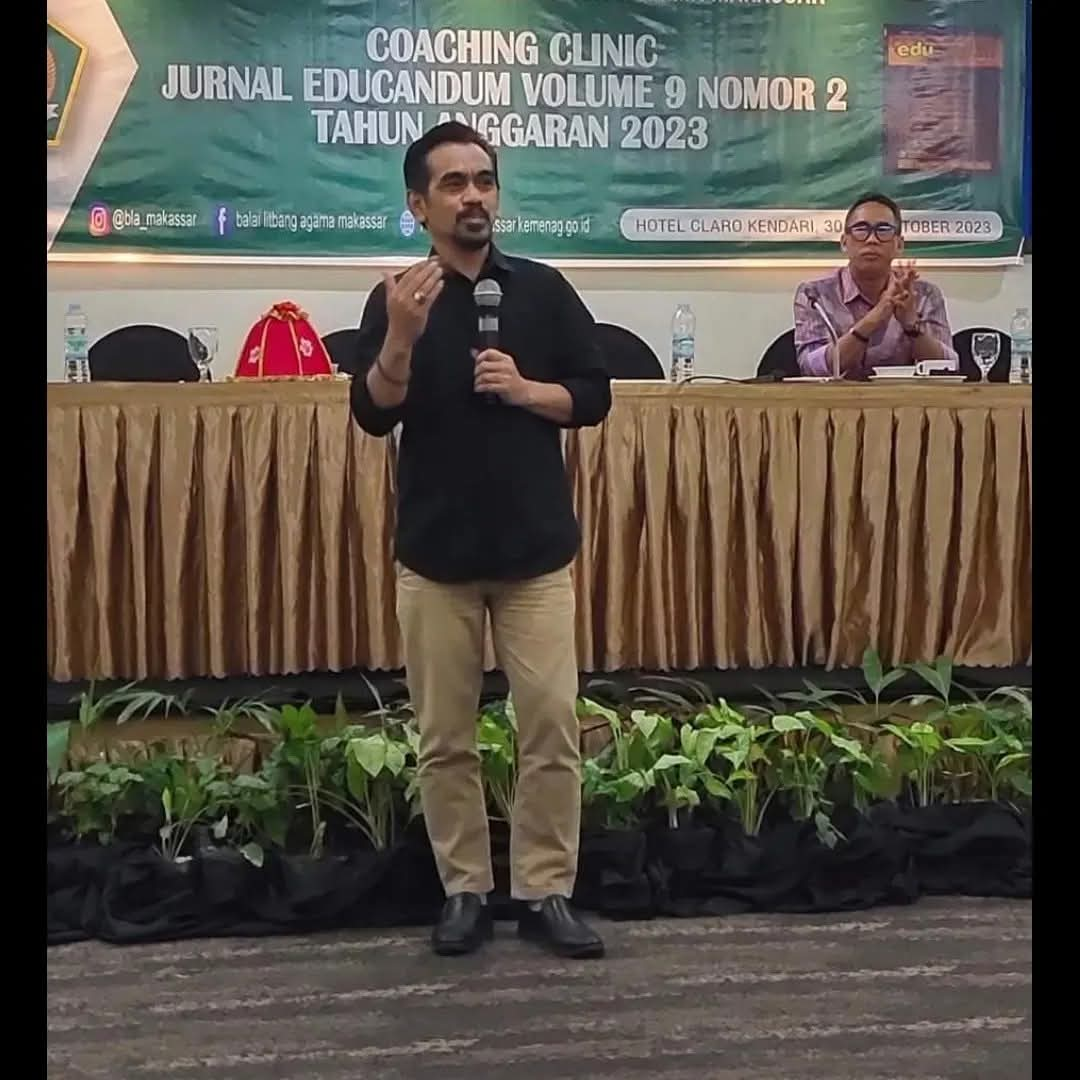
Pepi Al-Bayqunie/Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Refleksi atas Sambutan Menag pada Acara Peringatan Hari Bhakti Pertiwi Widyalaya
Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Nasaruddin Umar, tampaknya menaruh perhatian yang sangat serius pada gagasan ekoteologi. Dalam berbagai forum resmi Kementerian Agama, beliau secara konsisten memperkenalkan dan mengelaborasi konsep ini. Hampir setiap sambutan selalu membicarakan relasi agama dan lingkungan sebagai tema utama atau tema sisipan.
Ketika membuka rangkaian Hari Bhakti Pertiwi Widyalaya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu di UNHI (Universitas Hindu Indonesia) Denpasar Bali, tanggal 12 Pebruari 2026, Menteri Agama sekali lagi menjadikan tema ekoteologi sebagai menu utama pembicaraan.
Sebagaimana diakui oleh beliau, ekoteologi pada mulanya merupakan gagasan akademik yang abstrak. Ia lahir dari refleksi teologis mengenai relasi Tuhan, manusia, dan alam. Beberapa kolega pak Menteri mempertanyakan. Bagaimana wacana akademik dibawa masuk ke ranah administratif? Pendekatan di Kementerian tentu sangat berbeda dengan pendekatan di kampus.
Dengan konsistensi yang tinggi selama setahun kepemimpinan Menteri Agama, pelan tetapi pasti gagasan ekoteologi mulai menemukan artikulasi praksisnya. Ia bisa diterjemahkan ke dalam orientasi pembinaan, narasi kebijakan, hingga desain pendidikan keagamaan yang bersifat praksis. Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama kini semakin akrab dengan perspektif ekologis. Bahasa lingkungan tidak lagi berada di pinggir sambutan seremonial, tetapi masuk ke dalam struktur kesadaran institusional. Dari sinilah tampak bahwa ekoteologi tidak berhenti sebagai diskursus, melainkan bergerak menjadi arah nilai yang menuntun kebijakan.
Gagasan fundamental gerakan Ekoteologi, sebagaimana ditegaskan Menteri Agama, berangkat dari paradigma setiap agama yang sesungguhnya memiliki konsep trias relasi Tuhan–manusia–alam. Namun dalam praktik peradaban modern, relasi ini tidak lagi beroperasi secara utuh. Spritualitas tidak menjadi inspirasi pengelolaan alam. Spritual berjalan sendiri di ranah keagamaan, sedangkan pengelolaan alam dijalankan dengan logika ekonomi dan teknologi.
Krisis ekologis hari ini diawali dari krisis cara pandang terhadap lingkungan. Modernitas yang menjadi paradigma global membentuk cara pandang yang instrumental dan pragmatis. Alam diukur berdasarkan nilai ekonominya. Manusia sebagai subjek utama dan alam sebagai objek. Manusia sebagai pengguna, lingkungan sebagai penyedia. Sebenarnya, cara pandang ini normal. Tetapi karena dilakukan secara berlebihan, cara pandang ini menjadi sumber kerusakan alam. Pemanfaatan berubah menjadi eksploitasi. Pohon dinilai dari manfaat ekonominya saja, bukan dari posisinya dalam ekosistem kehidupan. Hutan menjadi angka statistik. Sungai menjadi saluran distribusi. Tanah menjadi komoditas. Akibatnya penebangan dilakukan tanpa mempertimbangkan ekosistem. Lingkungan mengalami desakralisasi parah.
Ketegangan yang sama terlihat dalam dunia pendidikan. Rasionalitas teknokratis berkembang pesat, tetapi kepekaan ekologis melemah. Kita unggul dalam kalkulasi, tetapi kurang dalam intuisi. Padahal nenek moyang kita memiliki kecerdasan ekologis yang lahir dari persahabatan panjang dengan alam. Mereka tidak memerlukan laboratorium untuk membaca kesuburan tanah; cukup dengan mencium tanah mereka memahami kondisinya. Mereka tidak membutuhkan radar untuk merasakan perubahan arus; sentuhan kaki pada air sudah cukup untuk menangkap tanda bahaya. Itu bukan anti-ilmu, melainkan bentuk pengetahuan yang tumbuh dari relasi yang intim dan berkelanjutan dengan lingkungan.
Di sinilah kebutuhan akan perjumpaan menjadi penting. Teknologi tidak ditolak, tetapi ditempatkan berdampingan dengan kearifan lokal. Efisiensi tidak dihapus, tetapi dilengkapi oleh empati. Universitas dan lembaga pendidikan diharapkan mampu menjembatani keduanya, sehingga modernitas tidak melahirkan keterasingan ekologis.
Dalam konteks Bali dan ajaran Hindu, konsep Tri Hita Karana memperlihatkan bagaimana kesadaran ekologis menyatu dalam praktik spiritual. Relasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika relasi dengan alam terganggu, keseimbangan spiritual pun ikut goyah. Perspektif ini memperlihatkan bahwa menjaga alam bukan aktivitas tambahan di luar ibadah, melainkan bagian inheren dari ibadah itu sendiri.
Ekoteologi yang digagas Kementerian Agama dapat dipahami sebagai upaya resakralisasi. Menghadirkan kembali sakralitas dalam cara manusia memandang alam. Bumi bukan sekadar ruang produksi, tetapi ruang perjumpaan antara ciptaan dan Pencipta. Ketika pohon kembali dipahami sebagai akar kehidupan, hujan sebagai rahmat, tanah sebagai amanah, dan laut sebagai misteri yang patut dihormati, maka spiritualitas dan keberlanjutan ekologis bergerak dalam sirkulasi yang sama. Hingga manusia berada pada titik spiritual; menjaga bumi sebagai bagian penting dari proyek penyembahan kepada Tuhan.
Mungkin, ide ini tidak bisa terwujud dengan cepat. Tetapi, kita harus memulai. Langkah itu sudah dimulai oleh Pak Menag. Kita harus melanjutkannya!
Penulis : Jamaah Gusdurian, tinggal di Sulawesi Selatan yang lahir dengan nama Saprillah
- Penulis: Pepi Al-Bayqunie




























Saat ini belum ada komentar