Tak Ada Yang Integratif Dari “Epistemologi Integratif” dalam Paradigma Makuta Ilmu: Itu Kesesatannya
- account_circle Tarmizi Abbas
- calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
- visibility 645
- print Cetak

Ilustrasi Makuta (Mahkota pengantin pria di Gorontalo) - nulondalo.com
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tulisan Donald Tungkagi berjudul Menjelaskan “Makuta Ilmu” Tanpa Menyesatkan: Kritik atas Kritik Tarmizi Abbas (9/1) di nulondalo.com., sebagai tanggapan atas tulisan saya (8/1) setidaknya memuat tiga poin utama, yakni: (1) penjelasan historiografis makuta problematik karena tidak cukup valid dalam simbol makuta dalam paradigma epistemologi Makuta Keilmuan; (2) ketegangan antarpilar itu produktif, alih-alih saling menegasikan satu sama lain; (3) Makuta Ilmu berangkat dari epistemologi dekolonial. Jika mau diperas dalam satu kalimat, Donald berkesimpulan bahwa kritik saya gagal memahami Makuta Ilmu sebagai paradigma pengetahuan yang sebenarnya tetap relevan dan integral satu sama lain meski penuh ketegangan, sebab paradigma tersebut secara praksis adalah jembatan antarpilar: Tuhan, manusia (adat) dan alam semesta (theo-antropo-kosmosentris).
Tulisan ini adalah tanggapan terhadap kritik atas kritik Donald pada tulisan saya sebelumnya. Fokus saya dalam tulisan juga akan saya padatkan menjadi tiga bagian. Pertama terletak pada ketidakonsistenan klaim Donald soal makuta yang sebenarnya diakuinya sendiri berakar pada tradisi intelektual masyarakat Gorontalo, namun tiba-tiba menjadi tidak relevan dan valid ketika menjadi dasar paradigma Makuta Ilmu. Kedua adalah kontradiksi inheren antarpilar di dalam paradigma Makuta Ilmu yang dipaksakan dengan menghadirkan jembatan sebagaimana muncul di dalam paradigma integrasi-interkoneksi yang, bagi saya, justru menciptakan keselarasan semu. Ketiga adalah penggunaan dekolonisasi pengetahuan semena-mena; seakan-akan ketika Makuta Ilmu bisa berbicara soal pengetahuan lokal, maka ia telah representatif dan bisa diterima begitu saja, padahal, justru ia akan berakhir pada posisi kolonial.
Namun sebelum melompat terlalu jauh, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal. Pertama, ketika saya memproblematisasi tawaran Makuta Ilmu sebagai sebuah paradigma, tidak serta merta saya memproblematisasi visi eksplisit UIN Smart, melainkan mengkritisi argumentasinya, terutama klaim bahwa ia “persis sama”. Ini juga ingin menunjukkan bahwa Makuta Ilmu bukan satu-satunya tawaran, melainkan hanya salah satu—itupun dengan basis argumentasi yang sangat lemah. Karena itu, saya menghadirkan dekolonialitas sebagai alternatif. Kedua, saya memang tidak menyentuh falsafah adati hula-hula to sara’a, sara’a hula-hula to Qur’ani itu dengan sadar, tetapi bukan berarti kritik saya itu selektif dan abai. Justru karena itu akan membawa diskusi terlalu jauh, terlebih saya sendiri skeptis terhadap keberadaannya. Ketiga, persoalan saya bukan pada nama, melainkan pada kerangka konseptualnya. Dengan demikian, perdebatan soal kritik terhadap trademark akademik UIN Smart menjadi tidak relevan. Terakhir, saya sepakat bahwa kritik harus dibalas dengan kritik, bukan satir atau nyinyir.
Kekuatan Historiografi dalam Paradigma
Ketika Donald menyimpulkan bahwa argumen historis tidak cukup menunjukkan relevansinya terhadap “simbolisasi makuta dalam paradigma epistemologi Makuta Ilmu”, maka di titik itu ia telah mengingkari argumen kuncinya sendiri yang menjadi basis dari paradigma Makuta Ilmu. Di tulisan awal, Donald menulis dengan gamblang: “makuta adalah cerminan dari nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam tradisi intelektual masyarakat Gorontalo”. Kalimat ini justru menunjukkan aspek historis dari Makuta Ilmu yang, sadar atau tidak, diakui Donald sebagai hal yang esensial dan bukan komplementer dalam tawaran paradigmanya. Saya lantas mengkritisinya: makuta tidak sama sekali punya hubungan dengan tradisi intelektual Gorontalo. Saya bahkan menunjukkan menunjukkan fakta-fakta historis, perubahan dan dinamikanya. Jadi, kritik saya relevan dan atas dasar itulah saya memperdebatkannya. Sayangnya, Donald menganggap bahwa catatan-catatan yang saya berikan menambah kekayaan makna simbolis pada “Makuta Ilmu”. Padahal pandangan ini keliru. Saya menampakkan fakta-fakta itu untuk menunjukkan kelemahan makuta, dan karena itu lemah, maka ia tidak bisa menjadi basis argumentasi untuk menguatkan paradigma Makuta Ilmunya.
Saya juga paham, ketika UIN Suka Yogyakarta mencetuskan paradigma jaring laba-laba, tidak berarti mereka harus mencari akar historis laba-laba di dalam kesultanan Yogyakarta. Atau ketika UIN Alauddin Makassar muncul dengan konsep “Sel-Cemara Keilmuan”, itu tidak berarti harus mencari di pohon cemara mana sel-sel keilmuan itu berada. Namun kasus ini berbeda dengan Makuta Ilmu yang ditawarkan Donald, di mana ia memulainya dengan aspek historiografi makuta: berakar pada tradisi intelektual Gorontalo. Pertanyaan penting yang saya ingin ajukan lagi: memang, di mana akarnya? Itu yang harusnya ia jawab, bukan malah meminta saya menunjukkan relevansi argumen historis makuta dan bagaimana ia valid terhadap gagasan paradigma epistemology “Makuta Ilmu”. Ini problem mendasar dari logika, yakni beban pembuktian (burden of proof): ketika seseorang mengajukan satu klaim, maka ia harus memberikan bukti-bukti valid yang mendukung argumentasinya. Ini persis ketika UIN Surakarta muncul dengan paradigma “Gunungan Ilmu”, mereka berhasil membuktikannya dalam akar kultur Jawa: poros kosmos, siklus awal dan akhir, hingga keselarasan hierarkis antara alam, manusia dan Yang Ilahiah. Dengan begitu, validlah paradigma “Gunungan Ilmu” tersebut sebagai paradigma epistemologi UIN Surakarta karena ia berangkat dari argument historis yang kuat.
Donald juga tidak perlu bersusah payah mengutip Kuhn kalau ternyata, interpretasinya terhadap perkembangan sains di dalam The Structure of Scientific Revolution (1962), juga keliru. Pertama, paradigma Kuhn bukan alat untuk mengamati masalah-masalah ilmiah, melainkan melihat: (1) apa yang boleh disebut masalah; (2) bagaimana cara menyelesaikannya; (3) bagaimana komunitas ilmiah bekerja. Itulah sebabnya, ketika mendefinisikan “paradigma” pada 30-40 halaman pertama bukunya, Kuhn menulis bahwa paradigma adalah “seperangkat contoh, nilai, dan praktik yang diakui bersama oleh suatu komunitas, yang menentukan apa yang dianggap sebagai masalah dan bagaimana masalah itu diselesaikan.” Di titik ini, Kuhn menaruh fenomena masyaraat sebagai hal esensial yang berkembang dalam sejarah sebagai yang riil dan tidak bisa disebut “sebatas representasi historis yang kaku”—sebagaimana tulis Donald. Justru, sejarah dalam perkembangan paradigma a la Kuhnian adalah titik kunci memahami bagaimana paradigma pengetahuan berkembang dan bersitegang melalui normal science 🡪 anomali dan krisis 🡪 revolusi ilmiah. Makanya, bagi Kuhn, saintis itu bukan pemecah masalah (problem solver), melainkan pemecah teka-teki (puzzle solver).
Lantas bagaimana ini bertaut dengan makuta? Sedari awal, saya telah menyebut hal tersebut, bahwa hanya karena ia diletakan di kepala, bukan berarti makuta memiliki koherensi dengan tradisi intelektual masyarakat Gorontalo. Tradisi intelektual itu dibangun berdasarkan berbagai ketegangan-ketegangan di dalam sejarah perkembangan peradaban Gorontalo yang pada akhirnya melahirkan pandangan dunia, kebudayaan dan tradisi masyarakat lokal yang berubah-ubah. Dengan mengunci berbagai ketegangan ini lewat makuta—yang jelas-jelas telah dilepaskan dari makna asalinya di dalam struktur kebudayaan Gorontalo dan mengalami reifikasi sebagai objek dan simbol—maka yang terjadi sebetulnya adalah reduksionisme epistemik, alih-alih penjelasan komprehensif tentang teo-antropo-kosmosentris sebagaimana ingin dipertahankan Donald.
Falasi Genetik dan Ketegangan Antarpilar
Pada saat yang sama, falasi genetik yang disematkan kepada saya juga salah alamat. Ketika menyatakan bahwa “makuta adalah campur tangan Islam (jalur Ternate) dan Belanda” serta “makuta telah ada sejak zaman Eyato sebagai busana adat”, sebenarnya saya melakukan kritik genealogis dan sumber, bahwa: (1) makuta tidak lepas dari cara kolonial mengidentifikasi posisi seseorang lewat benda dan simbol; (2) makuta tidak ditemukan dalam kanon S.R. Nur yang secara komprehensif dan menjadi rujukan ultim ketika membahas tata hukum adat di masa Eyato. Dua hal ini sah dan bukan falasi genetik. Bagi pembaca yang bingung, falasi genetik itu sederhananya begini:
- Karena klaim A bersumber dari X yang salah, maka A sudah pasti salah.
Atau jika rumus ini diekstrapolasi ke dalam pernyataan:
- Karena antropologi digunakan oleh pemerintah kolonial, maka semua pengetahuan antropologi tidak valid.
Antropologi tidak serta merta invalid hanya karena ia digunakan para penjajah. Toh saya juga menggunakan kerangka analisis antropologi untuk membongkar narasi kolonial dalam Dayango, juga kok! Bedanya, kolonial menyebut Dayango sebagai praktik animis, saya menyebutnya Islami. Dalam kaitannya dengan makuta, saya juga tidak mengatakan bahwa itu tidak valid. Makuta itu ada dan riil. Dalam naskah Tata Cara Adat Gorontalo tahun 2007, itu bahkan tertulis “makuta diperkenalkan oleh Islam dan Kolonial … dengan mengganti Paluwala dari kerangka daun dan ranting”. Artinya, makuta memang ada. Yang justru saya problematisasi dan menyebutnya keliru adalah makuta tidak valid disebut sebagai “simbol pengetahuan” apalagi “berakar pada tradisi intelektual masyarakat Gorontalo” karena sejak awal, ia adalah cara kolonial dan Islam untuk mengidentifikasi dan menstratifikasi masyarakat dalam status sosial dan kuasa yang berbeda. Selanjutnya, makuta invalid karena sebagai paradigma epistemologi, tiap-tiap pilar yang Anda ajukan itu bersitegang satu-sama lain dan tidak mungkin didialogkan sebab secara kategorikal, ketiganya kontradiktif satu sama lain. Di titik ini, di mana letak falasi genetiknya?
Tentang kekeliruan kategorikal dalam konteks ketegangan antarpilar, sedari awal dan sampai saat ini, saya tetap kukuh pada pendirian bahwa teo-antropo-kosmosentris itu secara tegas saling menegasikan satu sama lain. Saya juga sadar bahwa ketiganya itu berbeda dan tidak sama jika diperbandingkan. Mungkin saja, kesalahpahaman terjadi saat saya menulis “ketika menyamakan kosmosentrisme dengan sara’a, maka yang sangat mungkin terjadi adalah ketumpangtindihan” Sebenarnya, kata menyamakan itu bukan berarti menyatakan dua kategori, yakni “kosmosentrisme” dan “teosentrisme” dalam satu definisi yang identik (kosmosentrisme = teosentrisme). Bukan, bukan begitu. Yang saya maksud “menyamakan” adalah “menyandingkan” dua kategori tersebut pada posisi yang sama sehingga memungkinkan keduanya berdialog. Pasalnya, kedua kategori tersebut, baik secara definisi hingga pada tingkat operasionalisasinya sangat berbeda pada tulisan sebelumnya. Saya bahkan memberikan contoh bahwa dalam kasus Dayango yang bewatak kosmosentris, seringkali “ditafsirkan” tidak sesuai dengan syariat Islam karena memang titik berangkatnya berbeda.
Ketika merespons kasus Dayango ini, Donald lantas menghadirkan satu term yakni jembatan sebagai jalan agar teosentrisme, antroposentrisme dan kosmosentrisme berjumpa. Justru, di sinilah masalah itu muncul. Logika jembatan tidak bisa digunakan jika memang keduanya sudah kontradiktif satu sama lain. Bagaimana jika nanti di tengah jembatan keduanya justru bakuhantam, alih-alih dialog, saling peluk dan jabat tangan? Benar memang tulis Donald, “syariat Islam, khususnya dalam tradisi fiqh, selalu mempertimbangkan maqashid (tujuan hukum), maslahah (keselamatan publik), dan konteks sosio-kultural”. Namun ia juga mestinya sadar bahwa proses pembentukan produk hukum Islam “yang responsif” itu selalu bergantung pada rezim dan status quo yang berkuasa. Ketika ia menyodorkan Fiqh Lingkungan dengan konsep ekoteologi sebagai contoh relevan, maka bagi saya, ia harusnya melihat bahwa pada saat yang sama, organisasi-organisasi keagamaan juga memegang konsesi-konsesi tambang yang berpotensi mengabaikan bahkan menegasikan berbagai prinsip “eko-teologi” yang diusung mereka sendiri. Bahkan dalam fenomena ini, maslahah direduksi menjadi masalah ekonomi, bukan ekologis dan kosmik. Di titik ini, bukankah yang terjadi adalah “keselarasan semu”?
Benarkah Makuta Ilmu berangkat dari Dekolonisasi Pengetahuan?
Jika benar Makuta Ilmu berangkat dari dekolonisasi pengetahuan, bagaimana kita bisa tahu itu benar-benar “dekolonisasi pengetahuan” alih-alih dominasi pengetahuan berkedok dekolonisasi? Apakah hanya dengan bilang bahwa dia berangkat dari manifestasi ABSSBK dan Buatulo Toulongo lewat Makuta Ilmu maka itu sudah berarti dekolonisasi pengetahuan? Sayangnya, Donald juga tidak memberikan penjelasan konkrit, alih-alih memberikan tugas tambahan dengan menulis “barangkali dari sini bisa dimulai pencarian teori baru yang lahir dari fenomena lokal Gorontalo”. Meskipun begitu, saya ngebet ingin menguji hal ini, misalnya dengan pertanyaan sederhana: jika terjadi perjumpaan antara dua identitas berbeda, yakni Islam dan tradisi Gorontalo, maka bagaimana Makuta Ilmu menjelaskannya secara dekolonial? Bagaimana ketegangan keduanya dipahami? Adakah yang mesti mengalah? Jika ada, yang mana? Mungkinkah terjadi kroscek balik tradisi Gorontalo terhadap Islam, sebagaimana Islam selalu melakukannya terhadap tradisi Gorontalo?
Pada konteks yang lain, alih-alih berakhir pada simbol, dekolonisasi itu butuh penjelasan yang berpihak. Itulah sebab pada tulisan sebelumnya, saya tidak terlalu pusing apakah ia nanti akan menjadi logo atau tidak; berikut tidak penting juga menyebutnya autentik. Apa yang saya tawarkan adalah alternatif pembacaan yang berpihak. Dengan menjelaskan Dayango sebagai sesuatu yang Islami, saya telah berupaya menantang, paling tidak dua kategorisasi mainstream seperti “agama” dan “Islam” yang, bagi saya, selama ini dipahami sebagai standar apakah sebuah praktik dan tradisi layak religius atau tidak; bahkan pada derajat tertentu, menjadi alat yang memarjinalisasi Dayango di ruang publik. Hal ini dicapai dengan, meminjam Mignolo dan Walsh (2018), pertama de-lingking: membebaskan pengetahuan lokal dari narasi dominan, baik Timur dan Barat (tidak cuma Barat), lalu re-lingking, dalam artian menghubungkannya dengan siapa pemilik pengetahuan sebenarnya. Di titik itulah, paradigma secara efektif bekerja.
Toh pada dasarnya, logo institusi yang diklaim telah dekolonial juga tidak selalu berkorelasi dengan praktik akademik di kampus yang berpihak, adil dan setara. Jadi, meskipun kampus sudah menggunakan logo Makuta Ilmu yang syarat dengan theo-antropo-kosmosentrisme (dan diklaim Donald berangkat dari pendekatan dekolonial), namun kurikulumnya masih Euro-sentris, teori utamanya tetap kanon Barat atau Timur, relasi kuasa mahasiswa dan dosen tidak berubah, dan riset-riset lokal masih menjadi “objek” dan bukan kerangka epistemologi, maka itu tidak berarti apa-apa sama sekali. Justru, secara logika, ini non-sequitur atau merupakan bentuk kecacatan logika ketika kesimpulan tidak mengikuti premisnya. Paling banter, jika tetap kukuh dengan ini, ketakutan saya justru ia menjadi symbolic substitution fallacy, bahwa simbol telah menggantikan praktik; bahwa ketika simbol telah dekolonial, maka sudah tidak cukup dekolonisasi secara praksis karena itu sudah diwakili simbol.***
Alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saat ini adalah mahasiswa PhD Anthropology di The Australian National University.
- Penulis: Tarmizi Abbas
- Editor: Tarmizi Abbas






















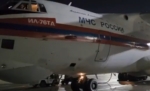




Saat ini belum ada komentar